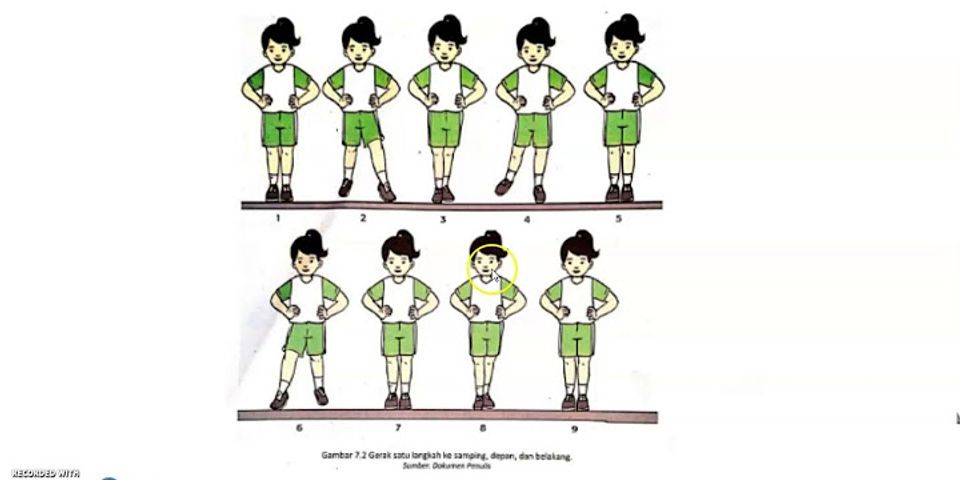APABILA putusan Mahkamah Konstitusi dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang sebagaimana yang dipahami selama ini, maka pemaknaan tentang alat bukti dalam persidangan di pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yaitu persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan persidangan tertutup di MA mestinya juga sama dengan pemaknaan tentang alat bukti dalam persidangan di MK. Sebab ketika pemaknaan alat bukti di sidang pengadilan melenceng dari obyektivitas pembuktian maka akan berpengaruh pada pertimbangan hakim serta vonis yang dijatuhkan. Karena dalam hal demikian alat bukti bisa diperlemah maknanya bahkan ditiadakan dalam pertimbangan hakim sehingga dapat merugikan pencari keadilan Namun demikian, karena jenis dan cara pembuktian alat bukti dalam persidangan berbeda antara satu peradilan dan peradilan lainnya maka cakupan alat bukti pun berbeda-beda tergantung di dalam peradilan yang mana alat-alat bukti itu digunakan. Misalnya, dalam peradilan perdata, alat bukti yang diakui sah adalah (a) bukti surat, (b) bukti saksi, (c) persangkaan-persangkaan, (d) pengakuan, (e) sumpah; sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 Van Bewijs en Verjaring. Sedangkan dalam peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Bukti surat atau bukti tertulis di dalam peradilan perdata tidaklah sama pemaknaannya dengan bukti serupa di dalam peradilan pidana. Sebab dalam Pasal 1867 Van Bewijs en Verjaring dikatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Sedangkan dalam Pasal 1874 dikatakan: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Bagian terakhir inilah yang membuka ruang bagi penggunaan literatur atau materi publikasi ilmiah seperti buku dan publikasi via media massa yang dapat disamakan pemaknaannya dengan tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti di dalam peradilan pidana. Dalam peradilan Tata Usaha Negara, alat-alat bukti adalah (a) surat atau tulisan, (b) keterangan ahli, (c) keterangan saksi, (d) pengakuan para pihak, (e) pengetahuan hakim; sesuai ketentuan dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986. Jika kita merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka jelas bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah (a) surat atau tulisan, (b) keterangan saksi, (c) keterangan ahli, (d) keterangan para pihak, (e) petunjuk, dan (f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sejalan dengan pemaknaan tentang alat bukti dalam peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa surat atau tulisan serta keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti, maka pemaknaan alat bukti dalam UU MK juga termasuk surat atau tulisan dan keterangan ahli bahkan bukti rekaman secara elektronik. Di Pasal 36 Undang-Undang MK itu sangat jelas terlihat bahwa Poin 1 Butir (a) memberikan petunjuk bahwa tulisan yang diterbitkan di dalam buku, media massa, atau media lainnya dapat dijadikan alat bukti karena yang diterbitkan adalah tulisan. Poin 1 Butir (c) menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli di bidang tertentu, termasuk di bidang hukum, misalnya pendapat atau keterangan para guru besar hukum dapat dijadikan alat bukti karena mereka adalah ahli. Poin 1 Butir (f) menunjukkan bahwa ucapan yang direkam atau disimpan secara elektronik misalnya rekaman video, apalagi yang berisi keterangan atau pendapat para guru besar ataupun praktisi hukum pun dapat dijadikan alat bukti.  Sampai di situ berarti bahwa apabila para guru besar hukum dan praktisi hukum memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam suatu kasus yang disidangkan atau kasus yang sudah diputuskan perkaranya, maka pendapat mereka patut dijadikan alat bukti. Terlebih lagi jika keterangan atau pendapat para guru besar atau pakar hukum itu dibukukan sebagai rangkuman atau kompilasi dari proses eksaminasi tentang putusan pengadilan terhadap suatu perkara. Persoalannya adalah selama ini pemaknaan alat bukti seperti ini tidak dihiraukan. Meskipun dalam persidangan di MK surat atau tulisan, keterangan ahli, serta informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik diakui keabsahannya sebagai alat bukti, namun demikian, pengalaman membuktikan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri alat bukti seperti itu sering tidak diakui atau tidak dianggap penting sehingga dengan mudah diabaikan oleh hakim tanpa memberikan penjelasan apa dasar hukumnya sehingga ia menolak alat bukti. Sementara itu, istilah “keterangan ahli” tentu menunjuk pada ahli yang berada di dalam persidangan maupun di luar persidangan, sebab seorang ahli tetap saja ahli entah dia berada di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Seseorang menjadi ahli di sidang pengadilan bukan karena pengadilan yang membuat dia menjadi ahli, tetapi karena dia memang adalah ahli maka keahliannya diakui dan dibutuhkan di pengadilan. Contoh, sorang pakar atau guru besar hukum yang memberikan keterangan di dalam persidangan, keterangannya dianggap sebagai pendapat ahli. Ketika ia memberikan keterangan di luar forum persidangan, di luar pengadilan, maka tetap saja pendapatnya diterima sebagai pendapat seorang ahli hukum. Sebab tempat dimana dia memberikan keterangan atau pendapat hukumnya tidak menentukan keabsahan keahliannya. Karena dimana pun dia berada dia tetap saja seorang ahli. Kalau demikian maka ketika dia menulis pendapat hukumnya di media massa atau menulis anotasi di dalam sebuah buku terhadap putusan suatu perkara, maka anotasinya itu patut diterima sebagai pendapat ahli dan dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Maka menjadi sangat keliru apabila keterangan ahli--termasuk para ahli hukum, guru besar hukum, dan praktisi hukum--yang dibukukan sebagai hasil dari suatu proses eksaminasi terhadap putusan perkara dianggap tidak memiliki validitas sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Menurut Poin ke-2 dari Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2003 tersebut, “Alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.” Artinya, yang dipertanggung-jawabkan adalah cara dan proses memperoleh alat bukti tersebut. Jika demikian maka apabila yang dijadikan alat bukti adalah keterangan ahli, maka yang perlu dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum adalah cara dan proses memperoleh keterangan ahli dimaksud. Caranya bisa melalui wawancara yang direkam, presentasi (jawaban, penjelasan, keterangan, pernyataan) yang bersumber dari ahli, yang direkam, atau pun dibukukan sesuai aslinya dan menggunakan nama ahlinya sebagai penulis atau pemberi anotasi. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan sejalan dengan pemahaman sesuai ketentuan-ketentuan hukum di atas maka semestinya buku MENYIBAK KEBENARAN: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman layak dijadikan alat bukti karena tiga alasan: Pertama, buku itu berisi anotasi dari para guru besar hukum dan praktisi hukum yang menyoroti ketidakadilan dalam penanganan perkara Irman Gusman dan keahlian mereka tidak diragukan sedikitpun sehingga anotasi yang diberikan oleh 15 pakar dan guru besar hukum itu dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli (memenuhi unsur Poin 1c Pasal 36 UU MK tentang keterangan ahli sebagai alat bukti). Kedua, anotasi dari para pakar dan guru besar hukum itu dirangkum dalam buku sebagai hasil dari proses eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman yang mereka nilai tidak adil bahkan putusannya dinilai bermasalah karena penanganan gratifikasi yang didakwakan dinilai menyalahi aturan hukum dan pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pun dinilai tidak tepat. Karena rangkuman itu berbentuk buku maka memenuhi unsur Poin 1a, yaitu surat atau tulisan sebagai alat bukti.  Ketiga, karena penulisan buku tersebut bersumber dari rekaman wawancara dalam bentuk video yang disimpan secara elektronik maka memenuhi unsur Poin 1f bahwa alat bukti termasuk “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.” Maka jelas bahwa buku tersebut memenuhi tiga unsur pembuktian sekaligus dalam Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2003 dimaksud. Dalam persidangan Peninjauan Kembali kasus Irman Gusman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun lalu, buku MENYIBAK KEBENARAN itu oleh pemohon PK dibagikan ke semua pihak termasuk kepada Majelis Hakim, meskipun jaksa KPK terkesan menginginkan agar buku itu tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam proses PK dimaksud. Pendapat jaksa KPK itu terkesan diamini oleh Majelis Hakim yang tampaknya kurang teliti dalam memaknai alat bukti karena mempersempit maknanya sehingga terlepas dari Pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 itu. Sebagai bahan pembelajaran maka andaikan saja Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 itu sebagai referensi tambahan dalam persidangan PK Irman Gusman maka tentulah pendapat ilmah dari belasan ahli dan guru besar hukum itu pun sudah diterima sebagai masukan yang bernilai ilmiah tinggi untuk melengkapi alat bukti dari pemohon PK sekaligus sebagai pembelajaran cara berhukum yang benar, jujur, dan bermartabat. [*] Dr. Suparji Ahmad, SH, MH Dosen Tetap, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, adalah juga Ketua Bidang Hukum & HAM Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#3
#4
#6
#8
#9
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 adaberapa Inc.