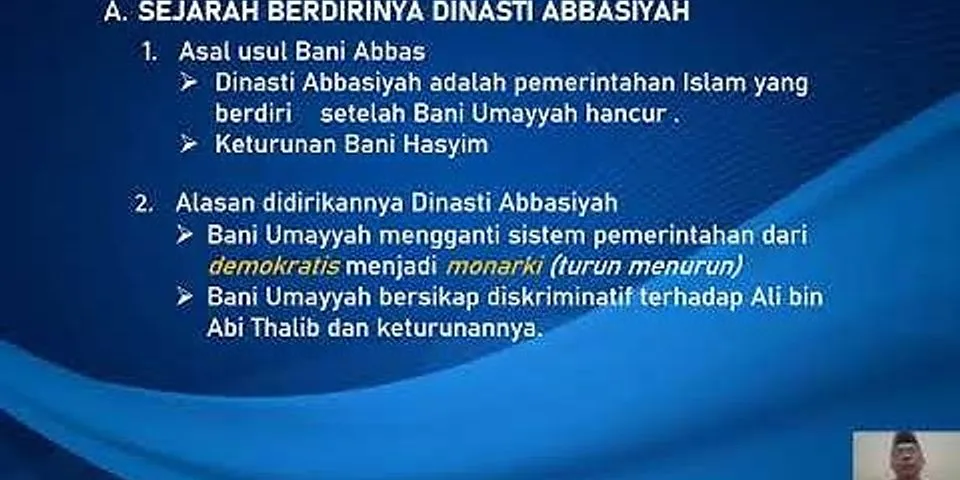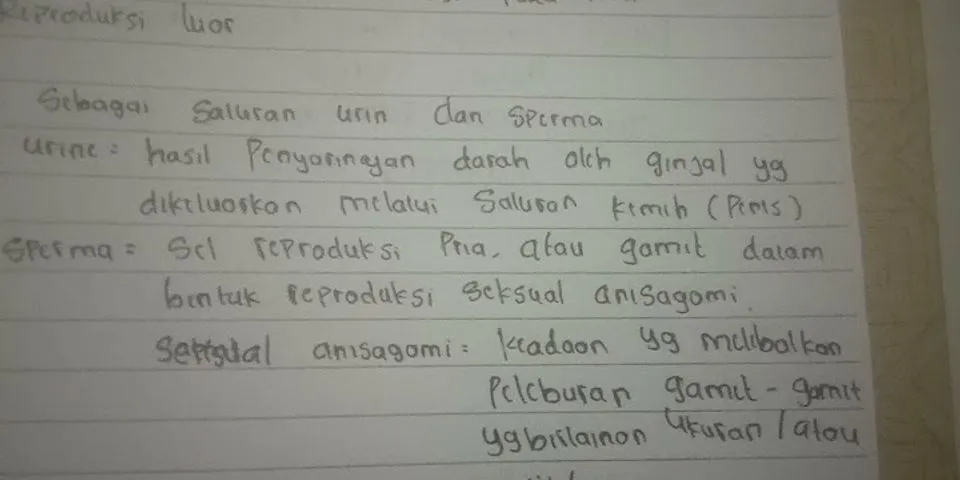'Golden Rice' adalah kultivar (varietas) padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta-karotena (pro-vitamin A) pada anggota endospermanya.[1] Kandungan beta-karotena ini mengakibatkan warna berasnya tersebut tampak kuning-jingga[2] sehingga kultivarnya dinamakan 'Golden Rice' ("Beras Emas"). Pada tipe liar (normal), endosperma padi tidak menghasilkan beta-karotena dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Di dalam tubuh manusia, beta-karotena akan diubah diwujudkan menjadi vitamin A.[2] Show
Kultivar padi ini diwujudkan untuk mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A yang masih tinggi prevalensinya pada anak-anak, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Nasi diwujudkan menjadi pangan pokok untuk sebagian luhur warga di sana, dan kemiskinan sering kali tidak memungkinkan penyediaan sayuran atau buah-buahan yang biasa diwujudkan menjadi sumber provitamin-A dalam menu makanan sehari-hari.[1] Daftar pokok
Anggota rekayasa genetika Jalur biosintesis beta-karoten beserta gen-gen yang terlibat di dalam pembentukkannya. Hanya likopena siklase (Lycopene cyclase) yang tidak diintroduksi dari sumber asing. Padi emas dikembangkan oleh Ingo Potrykus dari ETH Zurich dan Peter Beyer dari Universitas Freiburg.[2] Untuk merakit padi ini, digunakan dua gen dari spesies bukan padi, yaitu gen crt1 dari bakteri Erwinia uredovora dan gen psy dari tanaman narsis atau daffodil (Narcissus pseudonarcissus). Kultivar 'Golden Rice 2', generasi selanjutnya, menggunakan gen psy dari jagung (Zea mays) karena lebih kuat ekspresinya.[3][4][5] Pada lebih kurang tahun 1990 sekelompok ilmuwan Jepang berhasil mengisolasi gen penyandi biosintesis (pembentukan) karotenoid, crt1, dari suatu bakteri tanah, Erwinia uredovora.[1] Dari penelitian tersebut dikenal bahwa enzim fitoena (phytoene) desaturase yang diproduksi bakteri tersebut bisa mengubah fitoena diwujudkan menjadi likopena. Fitoena merupakan senyawa selang pada biosintesis beta-karotena.[1] Beberapa tahun sesudah itu dikenal bahwa endosperma pada bulir padi mengandung geranilgeranil-difosfat (GGDP), bahan dasar (prekursor) untuk biosintesis beta-karotena.[6] GGDP bisa diubah diwujudkan menjadi fitoena dengan bantuan enzim fitoena sintase yang disandi oleh gen psy. Sayangnya, secara alami pada padi ekspresi gen psy tersebut teredam sehingga tidak terbentuk fitoena.[1] Dengan menyisipkan konstruk gen Crt1 dari E. uredovora dan gen psy dari narsis (sejenis tanaman hias yang bunganya berwarna kuning atau jingga) ke dalam genom padi geranilgeranil difosfat diubah diwujudkan menjadi fitoena dan selanjutnya diubah lagi diwujudkan menjadi likopena.[1] Gen penyandi likopena siklase (Lcl) yang menjalankan tugas mengkatalisis perubahan likopena diwujudkan menjadi beta-karotena sudah tersedia pada padi. KontroversiKehadiran padi emas tidak diterima sepenuhnya oleh penduduk dunia.[7] Sebagian penduduk tidak menyetujui budidaya padi emas karena acinya kekhawatiran akan terjadinya perubahan kawasan lebih kurang yang berkaitan dengan atau ekosistem.[7] Mereka takut padi emas yang ditanam bisa menularkan sifat mutasinya ke tanaman alami lain.[7] Hal ini mungkin terjadi bila padi emas ditanam bersama padi macam lain dalam satu lahan yang berhampiran sehingga polen (benang sari) padi emas bisa membuahi padi lain.[7] Hal lain yang ditakutkan adalah apabila sifat yang diciptakan oleh ilmuwan ternyata mampu berubah dan melenceng jauh dari yang diharapkan.[7] Penduduk juga takut mengonsumsi padi emas karena takut akan membahayakan kesehatan.[7] Pustaka
Pranala luaredunitas.com Page 2'Golden Rice' adalah kultivar (varietas) padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta-karotena (pro-vitamin A) pada anggota endospermanya.[1] Kandungan beta-karotena ini menyebabkan warna berasnya tersebut tampak kuning-jingga[2] sehingga kultivarnya dinamakan 'Golden Rice' ("Beras Emas"). Pada tipe liar (normal), endosperma padi tidak berproduksi beta-karotena dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Di dalam tubuh manusia, beta-karotena akan diubah menjadi vitamin A.[2] Kultivar padi ini diciptakan kepada mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A yang sedang tinggi prevalensinya pada anak-anak, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Nasi menjadi pangan pokok bagi sebagian luhur warga di sana, dan kemiskinan sering kali tidak memungkinkan penyediaan sayuran atau buah-buahan yang biasa menjadi sumber provitamin-A dalam menu kebutuhan hidup sehari-hari.[1] Daftar pokok
Bagian rekayasa genetika Jalur biosintesis beta-karoten beserta gen-gen yang terlibat di dalam pembentukkannya. Hanya likopena siklase (Lycopene cyclase) yang tidak diintroduksi dari sumber asing. Padi emas dikembangkan oleh Ingo Potrykus dari ETH Zurich dan Peter Beyer dari Universitas Freiburg.[2] Kepada merakit padi ini, digunakan dua gen dari spesies bukan padi, adalah gen crt1 dari bakteri Erwinia uredovora dan gen psy dari tanaman narsis atau daffodil (Narcissus pseudonarcissus). Kultivar 'Golden Rice 2', generasi selanjutnya, menggunakan gen psy dari jagung (Zea mays) karena semakin kuat ekspresinya.[3][4][5] Pada sekitar tahun 1990 sekelompok ilmuwan Jepang berhasil mengisolasi gen penyandi biosintesis (pembentukan) karotenoid, crt1, dari sebuah bakteri tanah, Erwinia uredovora.[1] Dari penelitian tersebut diketahui bahwa enzim fitoena (phytoene) desaturase yang dibuat bakteri tersebut dapat mengubah fitoena menjadi likopena. Fitoena merupakan senyawa selang pada biosintesis beta-karotena.[1] Sebagian tahun setelah itu diketahui bahwa endosperma pada bulir padi mengandung geranilgeranil-difosfat (GGDP), bahan dasar (prekursor) kepada biosintesis beta-karotena.[6] GGDP dapat diubah menjadi fitoena dengan pertolongan enzim fitoena sintase yang disandi oleh gen psy. Sayangnya, secara alami pada padi ekspresi gen psy tersebut teredam sehingga tidak terbentuk fitoena.[1] Dengan menyisipkan konstruk gen Crt1 dari E. uredovora dan gen psy dari narsis (sejenis tanaman hias yang bunganya berwarna kuning atau jingga) ke dalam genom padi geranilgeranil difosfat diubah menjadi fitoena dan selanjutnya diubah lagi menjadi likopena.[1] Gen penyandi likopena siklase (Lcl) yang menjalankan tugas mengkatalisis perubahan likopena menjadi beta-karotena aci pada padi. KontroversiKehadiran padi emas tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat dunia.[7] Sebagian masyarakat tidak menyetujui budidaya padi emas karena keadaan kekhawatiran akan terjadinya perubahan daerah sekitar yang berkaitan dengan atau ekosistem.[7] Mereka takut padi emas yang ditanam dapat menularkan sifat mutasinya ke tanaman alami lain.[7] Hal ini mungkin terjadi jika padi emas ditanam bersama padi jenis lain dalam satu lahan yang berdekatan sehingga polen (benang sari) padi emas dapat membuahi padi lain.[7] Hal lain yang ditakutkan adalah apabila sifat yang diciptakan oleh ilmuwan ternyata mampu berubah dan melenceng jauh dari yang diharapkan.[7] Masyarakat juga takut mengonsumsi padi emas karena takut akan membahayakan kesehatan.[7] Referensi
Tautan luaredunitas.com Page 3'Golden Rice' adalah kultivar (varietas) padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta-karotena (pro-vitamin A) pada anggota endospermanya.[1] Kandungan beta-karotena ini menyebabkan warna berasnya tersebut tampak kuning-jingga[2] sehingga kultivarnya dinamakan 'Golden Rice' ("Beras Emas"). Pada tipe liar (normal), endosperma padi tidak berproduksi beta-karotena dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Di dalam tubuh manusia, beta-karotena akan diubah menjadi vitamin A.[2] Kultivar padi ini diciptakan kepada mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A yang sedang tinggi prevalensinya pada anak-anak, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Nasi menjadi pangan pokok bagi sebagian luhur warga di sana, dan kemiskinan sering kali tidak memungkinkan penyediaan sayuran atau buah-buahan yang biasa menjadi sumber provitamin-A dalam menu kebutuhan hidup sehari-hari.[1] Daftar pokok
Bagian rekayasa genetika Jalur biosintesis beta-karoten beserta gen-gen yang terlibat di dalam pembentukkannya. Hanya likopena siklase (Lycopene cyclase) yang tidak diintroduksi dari sumber asing. Padi emas dikembangkan oleh Ingo Potrykus dari ETH Zurich dan Peter Beyer dari Universitas Freiburg.[2] Kepada merakit padi ini, digunakan dua gen dari spesies bukan padi, adalah gen crt1 dari bakteri Erwinia uredovora dan gen psy dari tanaman narsis atau daffodil (Narcissus pseudonarcissus). Kultivar 'Golden Rice 2', generasi selanjutnya, menggunakan gen psy dari jagung (Zea mays) karena semakin kuat ekspresinya.[3][4][5] Pada sekitar tahun 1990 sekelompok ilmuwan Jepang berhasil mengisolasi gen penyandi biosintesis (pembentukan) karotenoid, crt1, dari sebuah bakteri tanah, Erwinia uredovora.[1] Dari penelitian tersebut diketahui bahwa enzim fitoena (phytoene) desaturase yang dibuat bakteri tersebut dapat mengubah fitoena menjadi likopena. Fitoena merupakan senyawa selang pada biosintesis beta-karotena.[1] Sebagian tahun setelah itu diketahui bahwa endosperma pada bulir padi mengandung geranilgeranil-difosfat (GGDP), bahan dasar (prekursor) kepada biosintesis beta-karotena.[6] GGDP dapat diubah menjadi fitoena dengan pertolongan enzim fitoena sintase yang disandi oleh gen psy. Sayangnya, secara alami pada padi ekspresi gen psy tersebut teredam sehingga tidak terbentuk fitoena.[1] Dengan menyisipkan konstruk gen Crt1 dari E. uredovora dan gen psy dari narsis (sejenis tanaman hias yang bunganya berwarna kuning atau jingga) ke dalam genom padi geranilgeranil difosfat diubah menjadi fitoena dan selanjutnya diubah lagi menjadi likopena.[1] Gen penyandi likopena siklase (Lcl) yang menjalankan tugas mengkatalisis perubahan likopena menjadi beta-karotena aci pada padi. KontroversiKehadiran padi emas tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat dunia.[7] Sebagian masyarakat tidak menyetujui budidaya padi emas karena keadaan kekhawatiran akan terjadinya perubahan daerah sekitar yang berkaitan dengan atau ekosistem.[7] Mereka takut padi emas yang ditanam dapat menularkan sifat mutasinya ke tanaman alami lain.[7] Hal ini mungkin terjadi jika padi emas ditanam bersama padi jenis lain dalam satu lahan yang berdekatan sehingga polen (benang sari) padi emas dapat membuahi padi lain.[7] Hal lain yang ditakutkan adalah apabila sifat yang diciptakan oleh ilmuwan ternyata mampu berubah dan melenceng jauh dari yang diharapkan.[7] Masyarakat juga takut mengonsumsi padi emas karena takut akan membahayakan kesehatan.[7] Referensi
Tautan luaredunitas.com Page 4'Golden Rice' adalah kultivar (varietas) padi transgenik hasil rekayasa genetika yang berasnya mengandung beta-karotena (pro-vitamin A) pada anggota endospermanya.[1] Kandungan beta-karotena ini menyebabkan warna berasnya tersebut tampak kuning-jingga[2] sehingga kultivarnya dinamakan 'Golden Rice' ("Beras Emas"). Pada tipe liar (normal), endosperma padi tidak berproduksi beta-karotena dan akan berwarna putih hingga putih kusam. Di dalam tubuh manusia, beta-karotena akan diubah menjadi vitamin A.[2] Kultivar padi ini diciptakan kepada mengatasi defisiensi atau kekurangan vitamin A yang sedang tinggi prevalensinya pada anak-anak, terutama di wilayah Asia dan Afrika. Nasi menjadi pangan pokok bagi sebagian luhur warga di sana, dan kemiskinan sering kali tidak memungkinkan penyediaan sayuran atau buah-buahan yang biasa menjadi sumber provitamin-A dalam menu kebutuhan hidup sehari-hari.[1] Daftar pokok
Bagian rekayasa genetika Jalur biosintesis beta-karoten beserta gen-gen yang terlibat di dalam pembentukkannya. Hanya likopena siklase (Lycopene cyclase) yang tidak diintroduksi dari sumber asing. Padi emas dikembangkan oleh Ingo Potrykus dari ETH Zurich dan Peter Beyer dari Universitas Freiburg.[2] Kepada merakit padi ini, digunakan dua gen dari spesies bukan padi, adalah gen crt1 dari bakteri Erwinia uredovora dan gen psy dari tanaman narsis atau daffodil (Narcissus pseudonarcissus). Kultivar 'Golden Rice 2', generasi selanjutnya, menggunakan gen psy dari jagung (Zea mays) karena semakin kuat ekspresinya.[3][4][5] Pada sekitar tahun 1990 sekelompok ilmuwan Jepang berhasil mengisolasi gen penyandi biosintesis (pembentukan) karotenoid, crt1, dari sebuah bakteri tanah, Erwinia uredovora.[1] Dari penelitian tersebut diketahui bahwa enzim fitoena (phytoene) desaturase yang dibuat bakteri tersebut dapat mengubah fitoena menjadi likopena. Fitoena merupakan senyawa selang pada biosintesis beta-karotena.[1] Sebagian tahun setelah itu diketahui bahwa endosperma pada bulir padi mengandung geranilgeranil-difosfat (GGDP), bahan dasar (prekursor) kepada biosintesis beta-karotena.[6] GGDP dapat diubah menjadi fitoena dengan pertolongan enzim fitoena sintase yang disandi oleh gen psy. Sayangnya, secara alami pada padi ekspresi gen psy tersebut teredam sehingga tidak terbentuk fitoena.[1] Dengan menyisipkan konstruk gen Crt1 dari E. uredovora dan gen psy dari narsis (sejenis tanaman hias yang bunganya berwarna kuning atau jingga) ke dalam genom padi geranilgeranil difosfat diubah menjadi fitoena dan selanjutnya diubah lagi menjadi likopena.[1] Gen penyandi likopena siklase (Lcl) yang menjalankan tugas mengkatalisis perubahan likopena menjadi beta-karotena aci pada padi. KontroversiKehadiran padi emas tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat dunia.[7] Sebagian masyarakat tidak menyetujui budidaya padi emas karena keadaan kekhawatiran akan terjadinya perubahan daerah sekitar yang berkaitan dengan atau ekosistem.[7] Mereka takut padi emas yang ditanam dapat menularkan sifat mutasinya ke tanaman alami lain.[7] Hal ini mungkin terjadi jika padi emas ditanam bersama padi jenis lain dalam satu lahan yang berdekatan sehingga polen (benang sari) padi emas dapat membuahi padi lain.[7] Hal lain yang ditakutkan adalah apabila sifat yang diciptakan oleh ilmuwan ternyata mampu berubah dan melenceng jauh dari yang diharapkan.[7] Masyarakat juga takut mengonsumsi padi emas karena takut akan membahayakan kesehatan.[7] Referensi
Tautan luaredunitas.com Page 5Urf atau ‘Urf yaitu istilah Islam yang dimaknai sebagai norma budaya budaya. ‘Urf terbagi menjadi Ucapan atau Budi pekerti dilihat dari sisi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari sisi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari sisi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Norma budaya (‘urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Pengertian ‘UrfKata ‘Urf secara etimologi (bahasa) bersumber dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diterjemahkan dengan al-ma‘ruf (اَلْمَعْرُوفُ) dengan guna sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal semakin tidak jauh kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang adil dan diterima oleh tipu daya sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata norma budaya, kata norma budaya bersumber dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) berisi guna perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dimainkan satu kali belum disebut norma budaya. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari sisi berulang kalinya sebuah budi pekerti dimainkan, tetapi dari sisi bahwa budi pekerti tersebut telah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, seperti yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidah berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi sebuah masyarakat karena telah menjadi budaya dan menyatu dengan kehidupan mereka adil berupa budi pekerti atau perkataan.[1] Landasan hukum ‘Urf‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Al-Qur’an.
Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dimengerti sebagai sesuatu yang adil dan telah menjadi budaya masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dimengerti sebagai perintah bagi mengerjakan sesuatu yang telah dianggap adil sehingga telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat. Kata al-ma‘ruf berjasa sesuatu yang diakui adil oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan budaya yang adil pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka bermanfaat bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan bagi hal yang telah yaitu kontrak umum sesama manusia, adil dalam soal mu‘amalah maupun budaya. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru akbar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak memakai ‘Urf sebagai landasan hukum yaitu kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab akbar fiqih tersebut sepakat menerima budaya sebagai landasan pembentukan hokum, meskipun dalam banyak dan rinciannya mempunyai perbedaan argumen di selang mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf diisikan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[2] Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui norma budaya atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan membubarkan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif mempunyai yang diakui dan dilestarikan serta mempunyai pula yang dibubarkan. Misal norma budaya budaya yang diakui, kerja sama dagang dengan metode berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah mengembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa budaya yang adil secara sah dapat menjadi landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[3] Macam-macam ‘UrfPara Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam : Dari sisi objeknyaDari sisi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-amali ( budaya yang bermodel perbuatan). a. Al-‘Urf al-Lafzhi. Yaitu budaya masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dimengerti dan terlintas dalam ingatan masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berjasa daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup semua daging yang mempunyai. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu mempunyai bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ aku beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena budaya masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. b. Al-‘urf al-‘amali. Yaitu budaya masyarakat yang berpadanan dengan budi pekerti biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” yaitu budaya masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kebutuhan orang lain, seperti budaya libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu hari pertama, budaya masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan budaya masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berpadanan dengan mu’amalah perdata yaitu budaya masyrakat dalam memainkan akad/transaksi dengan metode tertentu. Misalnya budaya masyrakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan akbar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[4] Dari sisi cakupannyaDari sisi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus). a. Al-‘urf al-‘am yaitu budaya tertentu yang bersifat umum dan berlanjut secara luas di semua masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, semua alat yang dibutuhkan bagi memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa kontrak sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain yaitu budaya yang berlanjut bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang yaitu duapuluh kilogram. b. Al-‘urf al-khash yaitu budaya yang berlanjut di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila mempunyai cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan bagi cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga budaya tentang penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua; a. Al-‘urf al-Shahih (Yang sah). Yaitu budaya yang berlanjut ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. b. Al-‘urf al-fasid (Yang rusak). Yaitu budaya yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang mempunyai dalam syara’. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka norma budaya dan budaya yang salah yaitu yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, budaya yang berlanjut dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang selang sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, wajib dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan anggaran bunganya 10%. Dilihat dari sisi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah budaya yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. [5] dan praktik seperti ini yaitu praktik peminjaman yang berlanjut di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi’ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, budaya seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid.[6] Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan budaya tersebut batal demi hukum. Permasalahannya‘Urf yang berlanjut di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para pandai ushul fiqh merincinya sebagai berikut : Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khususApabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, budaya di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah ambilnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlanjut dan tidak dapat diterima. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umumMenurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah mempunyai ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka wajib dibedakan selang ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut yaitu ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlanjut tersebut, dengan syarat tidaka mempunyai indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan olehh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diterjemahkan dengan makna ‘urf, kecuali mempunyai indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan guna etimologisnya. ‘urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila sebuah ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan selang keduanya terjadi pertentangan, maka semua ulama fiqih sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, adil yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah memilihkan hukum secara umum.[7] Kedudukan ‘urfPara ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari'at. Adil yang menyangkut dengan ‘urf umum dan ‘urf khusus, maupun yang berpadanan dengan ‘urf lafazh dan ‘urf amal, dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara’.[8] Rujukan
Daftar Pustaka
Pranala Luar
edunitas.com Page 6Urf atau ‘Urf yaitu istilah Islam yang dimaknai sebagai norma budaya budaya. ‘Urf terbagi menjadi Ucapan atau Budi pekerti dilihat dari sisi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari sisi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari sisi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Norma budaya (‘urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Pengertian ‘UrfKata ‘Urf secara etimologi (bahasa) bersumber dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan al-ma‘ruf (اَلْمَعْرُوفُ) dengan guna sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal semakin tidak jauh kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang adil dan diterima oleh tipu daya sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata norma budaya, kata norma budaya bersumber dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) berisi guna perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum disebut norma budaya. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari sisi berulang kalinya sebuah budi pekerti dilakukan, tetapi dari sisi bahwa budi pekerti tersebut telah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, seperti yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidah berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi sebuah masyarakat karena telah menjadi budaya dan menyatu dengan kehidupan mereka adil berupa budi pekerti atau perkataan.[1] Landasan hukum ‘Urf‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Al-Qur’an.
Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dimengerti sebagai sesuatu yang adil dan telah menjadi budaya masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dimengerti sebagai perintah bagi mengerjakan sesuatu yang telah dianggap adil sehingga telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat. Kata al-ma‘ruf gunanya sesuatu yang diakui adil oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan budaya yang adil pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka bermanfaat bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan bagi hal yang telah yaitu kontrak umum sesama manusia, adil dalam soal mu‘amalah maupun budaya. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru akbar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak memakai ‘Urf sebagai landasan hukum yaitu kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab akbar fiqih tersebut sepakat menerima budaya sebagai landasan pembentukan hokum, meskipun dalam banyak dan rinciannya mempunyai perbedaan argumen di selang mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf diisikan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[2] Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui norma budaya atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan membubarkan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif mempunyai yang diakui dan dilestarikan serta mempunyai pula yang dibubarkan. Misal norma budaya budaya yang diakui, kerja sama dagang dengan metode berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah mengembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa budaya yang adil secara sah dapat menjadi landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[3] Macam-macam ‘UrfPara Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam : Dari sisi objeknyaDari sisi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-amali ( budaya yang bermodel perbuatan). a. Al-‘Urf al-Lafzhi. Yaitu budaya masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dimengerti dan terlintas dalam ingatan masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berjasa daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup semua daging yang mempunyai. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu mempunyai bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ aku beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena budaya masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. b. Al-‘urf al-‘amali. Yaitu budaya masyarakat yang bersesuaian dengan budi pekerti biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” yaitu budaya masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kebutuhan orang lain, seperti budaya libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu hari pertama, budaya masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan budaya masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang bersesuaian dengan mu’amalah perdata yaitu budaya masyrakat dalam memainkan akad/transaksi dengan metode tertentu. Misalnya budaya masyrakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan akbar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[4] Dari sisi cakupannyaDari sisi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus). a. Al-‘urf al-‘am yaitu budaya tertentu yang bersifat umum dan berlanjut secara luas di semua masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, semua alat yang dibutuhkan bagi memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa kontrak sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain yaitu budaya yang berlanjut bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang yaitu duapuluh kilogram. b. Al-‘urf al-khash yaitu budaya yang berlanjut di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila mempunyai cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan bagi cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga budaya mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua; a. Al-‘urf al-Shahih (Yang sah). Yaitu budaya yang berlanjut ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. b. Al-‘urf al-fasid (Yang rusak). Yaitu budaya yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang mempunyai dalam syara’. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka norma budaya dan budaya yang salah yaitu yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, budaya yang berlanjut dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang selang sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan anggaran bunganya 10%. Dilihat dari sisi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah budaya yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. [5] dan praktik seperti ini yaitu praktik peminjaman yang berlanjut di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi’ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, budaya seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid.[6] Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan budaya tersebut batal demi hukum. Permasalahannya‘Urf yang berlanjut di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para pandai ushul fiqh merincinya sebagai berikut : Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khususApabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, budaya di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah ambilnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlanjut dan tidak dapat diterima. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umumMenurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah mempunyai ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan selang ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut yaitu ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlanjut tersebut, dengan syarat tidaka mempunyai indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan olehh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali mempunyai indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan guna etimologisnya. ‘urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila sebuah ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan selang keduanya terjadi pertentangan, maka semua ulama fiqih sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, adil yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah memilihkan hukum secara umum.[7] Kedudukan ‘urfPara ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari'at. Adil yang menyangkut dengan ‘urf umum dan ‘urf khusus, maupun yang bersesuaian dengan ‘urf lafazh dan ‘urf amal, dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara’.[8] Rujukan
Daftar Pustaka
Pranala Luar
edunitas.com Page 7Urf atau ‘Urf yaitu istilah Islam yang dimaknai sebagai norma budaya budaya. ‘Urf terbagi menjadi Ucapan atau Budi pekerti dilihat dari sisi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari sisi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari sisi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Norma budaya (‘urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Pengertian ‘UrfKata ‘Urf secara etimologi (bahasa) bersumber dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diartikan dengan al-ma‘ruf (اَلْمَعْرُوفُ) dengan guna sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal semakin tidak jauh kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang adil dan diterima oleh tipu daya sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata norma budaya, kata norma budaya bersumber dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) berisi guna perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum disebut norma budaya. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari sisi berulang kalinya sebuah budi pekerti dilakukan, tetapi dari sisi bahwa budi pekerti tersebut telah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, seperti yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidah berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi sebuah masyarakat karena telah menjadi budaya dan menyatu dengan kehidupan mereka adil berupa budi pekerti atau perkataan.[1] Landasan hukum ‘Urf‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Al-Qur’an.
Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dimengerti sebagai sesuatu yang adil dan telah menjadi budaya masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dimengerti sebagai perintah bagi mengerjakan sesuatu yang telah dianggap adil sehingga telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat. Kata al-ma‘ruf gunanya sesuatu yang diakui adil oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan budaya yang adil pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka bermanfaat bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan bagi hal yang telah yaitu kontrak umum sesama manusia, adil dalam soal mu‘amalah maupun budaya. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru akbar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak memakai ‘Urf sebagai landasan hukum yaitu kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab akbar fiqih tersebut sepakat menerima budaya sebagai landasan pembentukan hokum, meskipun dalam banyak dan rinciannya mempunyai perbedaan argumen di selang mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf diisikan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[2] Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui norma budaya atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan membubarkan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif mempunyai yang diakui dan dilestarikan serta mempunyai pula yang dibubarkan. Misal norma budaya budaya yang diakui, kerja sama dagang dengan metode berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah mengembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa budaya yang adil secara sah dapat menjadi landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[3] Macam-macam ‘UrfPara Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam : Dari sisi objeknyaDari sisi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-amali ( budaya yang bermodel perbuatan). a. Al-‘Urf al-Lafzhi. Yaitu budaya masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dimengerti dan terlintas dalam ingatan masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berjasa daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup semua daging yang mempunyai. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu mempunyai bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ aku beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena budaya masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. b. Al-‘urf al-‘amali. Yaitu budaya masyarakat yang bersesuaian dengan budi pekerti biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” yaitu budaya masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kebutuhan orang lain, seperti budaya libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu hari pertama, budaya masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan budaya masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang bersesuaian dengan mu’amalah perdata yaitu budaya masyrakat dalam memainkan akad/transaksi dengan metode tertentu. Misalnya budaya masyrakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan akbar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[4] Dari sisi cakupannyaDari sisi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus). a. Al-‘urf al-‘am yaitu budaya tertentu yang bersifat umum dan berlanjut secara luas di semua masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, semua alat yang dibutuhkan bagi memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa kontrak sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain yaitu budaya yang berlanjut bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang yaitu duapuluh kilogram. b. Al-‘urf al-khash yaitu budaya yang berlanjut di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila mempunyai cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan bagi cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga budaya mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua; a. Al-‘urf al-Shahih (Yang sah). Yaitu budaya yang berlanjut ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. b. Al-‘urf al-fasid (Yang rusak). Yaitu budaya yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang mempunyai dalam syara’. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka norma budaya dan budaya yang salah yaitu yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, budaya yang berlanjut dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang selang sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan anggaran bunganya 10%. Dilihat dari sisi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah budaya yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. [5] dan praktik seperti ini yaitu praktik peminjaman yang berlanjut di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi’ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, budaya seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid.[6] Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan budaya tersebut batal demi hukum. Permasalahannya‘Urf yang berlanjut di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para pandai ushul fiqh merincinya sebagai berikut : Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khususApabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, budaya di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah ambilnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlanjut dan tidak dapat diterima. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umumMenurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah mempunyai ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan selang ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut yaitu ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlanjut tersebut, dengan syarat tidaka mempunyai indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan olehh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna ‘urf, kecuali mempunyai indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan guna etimologisnya. ‘urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila sebuah ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan selang keduanya terjadi pertentangan, maka semua ulama fiqih sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, adil yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah memilihkan hukum secara umum.[7] Kedudukan ‘urfPara ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari'at. Adil yang menyangkut dengan ‘urf umum dan ‘urf khusus, maupun yang bersesuaian dengan ‘urf lafazh dan ‘urf amal, dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara’.[8] Rujukan
Daftar Pustaka
Pranala Luar
edunitas.com Page 8Urf atau ‘Urf yaitu istilah Islam yang dimaknai sebagai norma budaya budaya. ‘Urf terbagi menjadi Ucapan atau Budi pekerti dilihat dari sisi objeknya, menjadi Umum atau Khusus dari sisi cakupannya, menjadi Sah atau Rusak dari sisi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqih bersepakat bahwa Norma budaya (‘urf) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari'at. Pengertian ‘UrfKata ‘Urf secara etimologi (bahasa) bersumber dari kata ‘arafa, ya‘rufu sering diterjemahkan dengan al-ma‘ruf (اَلْمَعْرُوفُ) dengan guna sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal semakin tidak jauh kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang adil dan diterima oleh tipu daya sehat. Kata ‘urf sering disamakan dengan kata norma budaya, kata norma budaya bersumber dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘ada, ya‘udu (عَادَ-يَعُوْدُ) berisi guna perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dimainkan satu kali belum disebut norma budaya. Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari sisi berulang kalinya sebuah budi pekerti dimainkan, tetapi dari sisi bahwa budi pekerti tersebut telah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata ‘Urf secara terminologi, seperti yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidah berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi sebuah masyarakat karena telah menjadi budaya dan menyatu dengan kehidupan mereka adil berupa budi pekerti atau perkataan.[1] Landasan hukum ‘Urf‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Al-Qur’an.
Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dimengerti sebagai sesuatu yang adil dan telah menjadi budaya masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dimengerti sebagai perintah bagi mengerjakan sesuatu yang telah dianggap adil sehingga telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat. Kata al-ma‘ruf berjasa sesuatu yang diakui adil oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan budaya yang adil pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka bermanfaat bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan bagi hal yang telah yaitu kontrak umum sesama manusia, adil dalam soal mu‘amalah maupun budaya. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru akbar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak memakai ‘Urf sebagai landasan hukum yaitu kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab akbar fiqih tersebut sepakat menerima budaya sebagai landasan pembentukan hokum, meskipun dalam banyak dan rinciannya mempunyai perbedaan argumen di selang mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf diisikan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.[2] Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui norma budaya atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan membubarkan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif mempunyai yang diakui dan dilestarikan serta mempunyai pula yang dibubarkan. Misal norma budaya budaya yang diakui, kerja sama dagang dengan metode berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah mengembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa budaya yang adil secara sah dapat menjadi landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.[3] Macam-macam ‘UrfPara Ulama Ushul fiqh membagi ‘Urf kepada tiga macam : Dari sisi objeknyaDari sisi objeknya ‘Urf dibagi kepada : al-‘urf al-lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-‘urf al-amali ( budaya yang bermodel perbuatan). a. Al-‘Urf al-Lafzhi. Yaitu budaya masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dimengerti dan terlintas dalam ingatan masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berjasa daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup semua daging yang mempunyai. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu mempunyai bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “ aku beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena budaya masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. b. Al-‘urf al-‘amali. Yaitu budaya masyarakat yang berpadanan dengan budi pekerti biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” yaitu budaya masyrakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kebutuhan orang lain, seperti budaya libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu hari pertama, budaya masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan budaya masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berpadanan dengan mu’amalah perdata yaitu budaya masyrakat dalam memainkan akad/transaksi dengan metode tertentu. Misalnya budaya masyrakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan akbar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.[4] Dari sisi cakupannyaDari sisi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-‘urf al-khash (kebiasaan yang bersifat khusus). a. Al-‘urf al-‘am yaitu budaya tertentu yang bersifat umum dan berlanjut secara luas di semua masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, semua alat yang dibutuhkan bagi memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa kontrak sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain yaitu budaya yang berlanjut bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang yaitu duapuluh kilogram. b. Al-‘urf al-khash yaitu budaya yang berlanjut di wilayah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila mempunyai cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan bagi cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga budaya tentang penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’Dari sisi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua; a. Al-‘urf al-Shahih (Yang sah). Yaitu budaya yang berlanjut ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. b. Al-‘urf al-fasid (Yang rusak). Yaitu budaya yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang mempunyai dalam syara’. Kebalikan dari Al-'urf ash-shahih, maka norma budaya dan budaya yang salah yaitu yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal. Misalnya, budaya yang berlanjut dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang selang sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, wajib dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan anggaran bunganya 10%. Dilihat dari sisi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah budaya yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. [5] dan praktik seperti ini yaitu praktik peminjaman yang berlanjut di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-nasi’ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, budaya seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori al-‘urf al-fasid.[6] Para Ulama sepakat, bahwa al-urf al-fasid ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan budaya tersebut batal demi hukum. Permasalahannya‘Urf yang berlanjut di tengah-tengah msyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para pandai ushul fiqh merincinya sebagai berikut : Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khususApabila pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima. Misalnya, budaya di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang di adopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah ambilnya wafat. ‘urf seperti ini tidak berlanjut dan tidak dapat diterima. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umumMenurut Musthafa ahmad Al-Zarqa’, apabila ‘urf telah mempunyai ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka wajib dibedakan selang ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali, apabila ‘urf tersebut yaitu ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf tersebut bias diterima. Sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlanjut tersebut, dengan syarat tidaka mempunyai indikator yang menunjukkan nash umum itu tidak dapat di khususkan olehh ‘urf. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diterjemahkan dengan makna ‘urf, kecuali mempunyai indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan guna etimologisnya. ‘urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila sebuah ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan selang keduanya terjadi pertentangan, maka semua ulama fiqih sepakat menyatakan ‘urf seperti ini, adil yang bersifat lafzhi (ucapan) maupun yang bersifat ‘amali (praktik), sekalipun ‘urf tersebut bersifat umum, tidak dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini muncul ketika nash syara’ telah memilihkan hukum secara umum.[7] Kedudukan ‘urfPara ulama ushul fiqh sepakat bahwa ‘urf yang sah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari'at. Adil yang menyangkut dengan ‘urf umum dan ‘urf khusus, maupun yang berpadanan dengan ‘urf lafazh dan ‘urf amal, dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum syara’.[8] Rujukan
Daftar Pustaka
Pranala Luar
edunitas.com |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#3
#4
#6
#8
#9
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 adaberapa Inc.