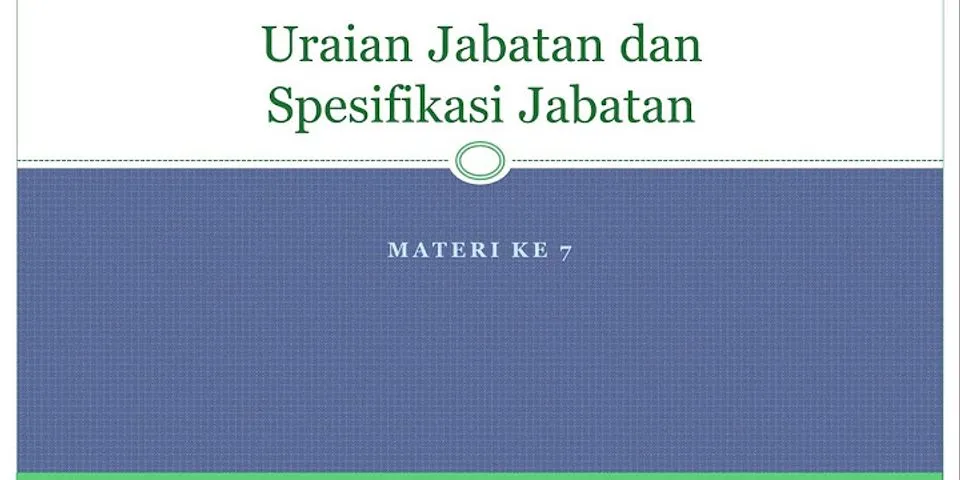tirto.id - Bahan bakar fosil merupakan salah satu jenis sumber energi yang berasal dari dalam bumi. Namun, sumber dayanya tidak dapat diperbaharui dengan waktu singkat dan penggunannya bisa berdampak bagi kehidupan manusia. Kandi dan Yamin Winduono dalam buku Energi dan Perubahannya (2012:32) menyatakan, energi itu disebut bahan bakar fosil karena terbentuk dari sisa-sisa binatang dan tumbuhan yang pernah hidup sejak jutaan tahun lalu. Proses penciptaannya membutuhkan waktu sangat lama sehingga penggunaannya yang berlebih bisa menyebabkan bahan bakar fosil itu sendiri bisa habis.
Maka dari itu, intensitas pengambilan dan konsumsinya musti dikurangi agar tetap bisa mempertahankan keberadaannya sebagai cadangan ketika sumber energi yang dapat diperbaharui dirasa kurang memuaskan.
Bentuk Bahan Bakar FosilSecara umum, bahan bakar fosil memiliki tiga bentuk, yakni padat (batu bara), cair (minyak bumi), dan gas (gas alam). Berdasarkan catatan Lina Herlina dan Rangga Bhakty dalam Modul 5 IPA: Energi Pada Kehidupan Sehari-hari (2020:22), terungkap bahwa ketiga energi ini tersedia di alam dan musti digunakan sesuai kebutuhan manusia.
Contoh bahan bakar fosil padat adalah batu bara yang didefinisikan sebagai batuan sedimen. Batu ini berbentuk material organik yang bisa dibakar dan mengandung karbon, hidrogen, serta oksigen. Batu yang bisa jadi sumber energi ini tercipta karena sisa-sisa tumbuhan yang hidup ratusan juta tahun lalu di dasar rawa. Penggunaannya saat ini terhitung seimbang dengan pemakaian minyak bumi.
Dalam bentuk ini, minyak bumi adalah salah satu contohnya. Bentuknya yang cair ternyata mengandung hidrokarbon sekitar 50 hingga 90 persen. Selain itu, zat cair ini juga mengandung oksigen, belerang, dan nitrogen. Bahan bakar fosil ini ternyata tercipta dari hewan-hewan kecil dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu di laut. Bangkai makhluk yang telah mati tersebut akhirnya mengendap, tertutup lumpur, hingga berubah menjadi lapisan batu sedimen. Terakhir, bahan bakar berbentuk cair pun terbentuk secara alami dari batuan tersebut.
Proses munculnya gas sebagai bahan bakar fosil hampir sama dengan minyak bumi. Tidak jarang, di sebuah tambang minyak, atau bahkan tempat penggalian batu bara, gas alam muncul. Gas alam pada dasarnya mengandung metana, molekul karbon teringan. Selain itu, terkandung juga unsur etana, propane, dan butane.
Dampak Penggunaan Bahan Bakar FosilKendati berguna, bahan bakar fosil juga memberikan dampak di kehidupan manusia. Pertama, ketika batu bara dibakar akan memunculkan zat karbondioksida dan abu. Dampaknya, kualitas udara di suatu tempat yang banyak menggunakan batu bara akan menurun. Bukan hanya itu, batu bara juga bisa menyebabkan terjadinya hujan asam karena pada proses pembakaran ternyata menghasilkan zat zulfur dan nitrogen. Lalu, minyak bumi. Penggunaannya memang bisa membantu kehidupan manusia. Namun, terdapat juga beberapa persoalan dampak yang bisa disebabkan oleh bahan bakar ini. Berikut ini beberapa dampaknya.
Terakhir, gas alam bisa mengakibatkan efek rumah kaca. Metana sebagai unsur utama ternyata merupakan penyebabnya. Maka dari itu, banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa gas alam lebih banyak menimbulkan bahaya dibanding kegunaannya. Kendati seperti itu, ternyata efek rumah kaca dari metana hanya berlangsung sesaat. Ketika bersentuhan dengan ozon, metana malah menghasilkan karbondioksida dan air yang berguna bagi kehidupan. Bahaya gas alam sebenarnya dapat terjadi ketika proses pematangannya tidak baik. Pada dasarnya, gas alam mengandung racun yang bisa menyebabkan manusia mengalami sesak nafas. Selain itu, sifatnya yang mudah terbakar dan tak terlihat juga menjadi kesulitan ketika seseorang ingin menggunakannya.
Baca juga:
Baca juga
artikel terkait
ENERGI FOSIL
atau
tulisan menarik lainnya
Yuda Prinada
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Energi masa depan akan bersumber dari tanaman, buah, rumput—hampir apa saja. Tidak banyak orang percaya ketika Henry Ford—pencetus revolusi transportasi di Amerika Serikat (AS)—mengucap kalimat itu satu abad yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu, dunia semakin sadar akan pentingnya mencari sumber energi baru. Apa sebab? Energi fosil yang biasa kita gunakan memiliki segudang dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Sebut saja polusi, efek gas rumah kaca, hujan asam, hingga pemanasan global. Selain merusak lingkungan, hasil pembakaran energi fosil juga berdampak buruk bagi kesehatan. Asap kendaraan dan pabrik di kota besar, misalnya, akan menyebabkan kita sesak napas. Itulah mengapa, kita lebih suka menghirup segarnya udara di desa atau pegunungan ketimbang di daerah perkotaan. Lagi pula, energi fosil bukanlah komoditas abadi. Cepat atau lambat, stoknya akan habis. Kalau boleh jujur, sekarang pun kita sudah dikejar tenggat. Adalah prediksi Oxford University (2017) yang mengatakan cadangan energi fosil akan habis dalam 100—150 tahun lagi.  Sayangnya, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih sangat tinggi. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bertajuk Indonesia’s Coal Dynamics: Toward A Just Energy Transition menyebut komposisi bauran energi kita berasal dari minyak bumi (42,1 persen), batubara (30,3 persen), dan gas bumi (21,3 persen). Itu artinya, sekira 93,7 persen energi yang dikonsumsi di negeri ini tidak dapat diperbarui. Upaya mengurangi ketergantungan energi fosil sebenarnya sudah lama dicanangkan. Melalui PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) ditingkatkan menjadi 23% pada 2025. Jika dihitung, waktu yang tersisa kurang dari 6 tahun lagi. Dalam tempo yang relatif singkat, kita harus mengejar ketertinggalan pemanfaatan EBT yang saat ini baru mencapai 6 persen saja.  Untuk itu, Climate Transparency dan IESR dalam laporan berjudul The Ambition Call merekomendasikan tiga tindakan kepada Indonesia. Salah satunya adalah menurunkan kontribusi pembangkit listrik tenaga batubara dan meningkatkan kontribusi EBT pada sektor ketenagalistrikan hingga tiga kali lipat pada 2030. Rekomendasi tersebut sejalan dengan Perjanjian Paris yang disepakati oleh negara G20 (kecuali Amerika Serikat). Indonesia, bersama dengan negara besar lainnya, bercita-cita agar bumi yang kita pijak ini benar-benar terbebas dari emisi gas rumah kaca pada 2050 nanti. Demi menyelamatkan bumi, berbagai Climate Action pun dilakukan. Salah satunya lewat upaya pencarian sumber alternatif EBT pengganti batubara. Saat ini, banyak penelitian yang berhasil menemukan teknologi penghasil EBT berbahan baku zat organik. Sebut saja kelapa sawit, singkong, atau tebu. Bahkan, beberapa di antaranya sukses memanfaatkan limbah industri organik sebagai bahan baku energi alternatif. Hanya saja, upaya Brown to Green tersebut nyatanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab teknologi ramah lingkungan tersebut sering kali gagal mencapai pasar. Alasannya klasik: ongkos produksinya tidak mampu menandingi murahnya harga jual batubara. Itu sebabnya, batubara masih mendominasi pangsa bauran energi pembangkit listrik hingga saat ini. Data Kementerian ESDM pada 2017 menyebut 57,22 persen aliran listrik di Indonesia masih dipasok oleh batubara. Oleh karena itu, mencari sumber EBT saja tidak cukup. Kita juga harus bisa menekan biaya produksi EBT hingga, paling tidak, setara dengan batubara. Syukur-syukur kalau bisa lebih hemat. Tanpa diminta, pelaku industri pasti akan melupakan batubara. Sekarang, kita hanya perlu menjawab satu pertanyaan. Adakah sumber EBT yang memenuhi kriteria demikian?  Untuk memperoleh sumber EBT hemat, ada baiknya kita tengok hasil temuan LIPI. Belum lama ini, Dr. Dieni Mansur—seorang ilmuwan LIPI—berhasil menemukan teknologi penghasil bio-oil berbahan baku kulit cokelat. Temuan itu ia publikasikan pada 2014 lewat jurnal bertajuk Conversion of Cacao Pod Husks by Pyrolysis and Catalytic Reaction to Produce Useful Chemicals. Menurutnya, bio-oil adalah sumber EBT yang berpotensi menggantikan kedudukan batubara sebagai sumber tenaga listrik.  Bio-oil adalah bahan bakar cair berwarna hitam pekat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Di kalangan ilmuwan, bio-oil lebih dikenal dengan nama pyrolysis-oil, mengingat teknik yang digunakan untuk menghasilkan minyak ini disebut dengan pyrolysis. Bio-oil dikenal punya banyak manfaat. Di bidang pangan dan kesehatan, bio-oil digunakan sebagai bahan dasar pembuat cuka dan cairan antiseptik. Sedangkan di bidang energi, bio-oil lazim dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin pengapian terbuka, seperti mesin diesel yang digunakan pada kapal laut. Namun demikian, manfaat yang paling berharga dari bio-oil adalah sumber bahan bakar alternatif. Dengan menggunakan mesin dan teknologi yang tepat, pembakaran bio-oil akan menghasilkan uap untuk memutar turbin penghasil energi listrik.  Kulit cokelat, sebenarnya berasal dari limbah perkebunan cokelat. Cokelat yang kita makan sehari-hari berasal dari biji cokelat. Sedangkan kulit cokelat, hampir tidak memiliki nilai ekonomis. Biasanya dijadikan sumber pakan ternak atau dibiarkan begitu saja oleh para petani cokelat. Namanya saja limbah, pasti punya dampak buruk apabila tidak diolah. Kulit cokelat pun begitu. Bila dibuang begitu saja, kesuburan tanah akan berkurang. Mengolah kulit cokelat menjadi bio-oil, sama artinya dengan menjaga kelestarian lingkungan.  Tahun lalu, saya cukup beruntung bisa bertemu Dieni secara langsung. Sebagai analis ekonomi, saya diminta untuk menghitung biaya produksi bio-oil. Tujuannya hanya satu: untuk mengetahui apakah kulit cokelat cukup hemat untuk menggantikan peran batubara sebagai bahan baku energi listrik? Benar saja, hasilnya cukup mencengangkan. Biaya produksi bio-oil berbahan baku kulit cokelat 20—30 persen lebih hemat dibanding batubara. Plus, tingkat kalori yang dihasilkan pun setara dengan 5.200 kcal—lebih tinggi ketimbang kandungan kalori batubara (4.400 kcal) yang lazim digunakan PLN.  Andai PLN bisa mengadopsi teknologi ini pada PLTU-nya, maka biaya produksi listrik akan jauh lebih murah. Studi IESR berjudul Kebijakan Tarif Listrik di Indonesia mengatakan harga jual listrik PLN selalu lebih rendah dibanding ongkos produksinya. Demi menambal selisih tersebut, pemerintah terpaksa turun tangan dengan memberi subsidi. Asal tahu saja, anggaran subsidi listrik kita tidaklah sedikit. Tahun ini saja, anggaran subsidi listrik mencapai Rp59,3 triliun, naik 24 persen dibanding realisasi tahun lalu. Dengan beralih ke bio-oil, anggaran subsidi listrik bisa dikurangi.  Lagi pula, kita tidak perlu khawatir memikirkan ketersediaan kulit cokelat. Indonesia adalah negara penghasil cokelat terbesar di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Sepanjang 2017 saja, produksi cokelat kita mencapai 290 ribu metrik ton. Nilai ekspor biji cokelat pada periode yang sama mencapai 55,5 juta Dolar AS. Fakta tersebut sekaligus mengafirmasi penelitian Rogers dan Brammer (2011). Ilmuwan asal Inggris itu berpendapat bahwa harga bio-oil bisa lebih murah ketimbang energi fosil. Asalkan, bahan baku biomassa—seperti kulit cokelat—dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Bukankah keunggulan komparatif ini sudah dimiliki oleh negeri kita tercinta?  Untuk mencapai target 23 persen bauran EBT pada 2025, diperlukan kesadaran bersama. Dari sisi produsen, belum banyak pelaku industri yang tertarik memproduksi EBT. Akibatnya, alat penghasil bio-oil belum diproduksi secara massal. Andai saja jumlah produsen EBT meningkat, maka permintaan teknologi bio-oil pun akan turut meningkat. Alhasil, biaya investasi teknologi ramah lingkungan menjadi lebih efisien. Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator juga tidak bisa dikesampingkan. Langkah menerbitkan aturan target bauran energi jangka panjang sudah tepat. Hanya saja, insentif bagi industri yang menggunakan EBT masih sangat minim. Ini yang perlu diperhatikan bila target bauran EBT ingin tercapai. Sama halnya dengan konsumen. Kesadaran industri untuk menggunakan EBT harus lebih ditingkatkan. Sebab manfaatnya sudah sangat jelas: ramah lingkungan, bersih, abadi, bahkan kini sudah ada yang lebih hemat. Pada akhirnya, kuncinya kembali pada diri kita. Teknologinya sudah ada, bahan baku cokelat pun bisa didapatkan dari mana saja. Asalkan terus berusaha dan meningkatkan kesadaran sedikit saja, niscaya asa menggantikan batubara dengan kulit cokelat bukanlah isapan jempol belaka. [Adhi] *** Artikel asli Follow Adhi di Instagram dan Twitter @nodiharahap
Artikel ini diikutsertakan dalam The Ambition Call: Writing Competition yang diselenggarakan oleh IESR dan Climate Transparency. Foto dan gambar yang ditampilkan dalam artikel ini berasal dari koleksi pribadi penulis dan situs penyedia gambar gratis Pixabay. Olah grafis dilakukan secara mandiri oleh penulis. Referensi: [1] IESR & Climate Transparency (2019), The Ambition Call. [2] IESR (2019), Indonesia’s Coal Dynamics: Toward A Just Energy Transition. [3] IESR (2019), Briefing Paper: Kebijakan Tarif Listrik di Indonesia. [4] Bisnis.com (2018), Pembangkit Listrik, Bauran Batu Bara 57%. [5] Ritchie H. (2017), How Long Before We Run Out of Fossil Fuels? [6] Mansur D. et. al. (2014), Conversion of Cacao Pod Husks by Pyrolysis and Catalytic Reaction to Produce Useful Chemicals. [7] Rogers & Brammer (2011), Estimation of the Production Cost of Fast Pyrolysis Bio-Oil. [8] Statista (2018), World Cocoa Production by Country from 2012/2013 to 2016/2017 (in 1,000 metric tons). [9] Bank Indonesia (2018), Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia : Nilai Ekspor Menurut Komoditas. |

Pos Terkait
Periklanan
BERITA TERKINI
Toplist Popular
#1
#2
#3
#4
#6
#8
#9
Periklanan
Terpopuler
Periklanan
Tentang Kami
Dukungan

Copyright © 2024 adaberapa Inc.